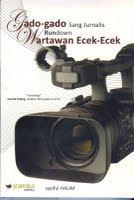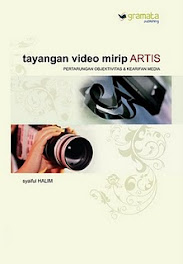Pemberitaan televisi kita soal bom di JW Marriott dan Ritz-Carlton dipenuhi dengan adu cepat berita serta "jurnalisme ludah" yang berisi omongan spekulatif, perbincangan konspiratif, dan pertanyaan klise yang kadang-kadang konyol.
Di antara semua stasiun televisi Indonesia, Metro TV yang paling cepat mengabarkan peristiwa peledakan bom di Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton pada Jumat, 17 Juli 2009 lalu. Hari itu, sebelum pukul 08.15, Metro sudah menyiarkan bahwa ada ledakan di Hotel Ritz-Carlton. Pertama kali berita dikabarkan lewat mata acara Headline News, lalu disusul acara berita khusus bertajuk Breaking News. Sebagai televisi berita, Metro terbiasa menghadapi peristiwa-peristiwa tak biasa semacam ini dengan membuat "acara dadakan" yang durasinya panjang dan isinya khusus membahas satu peristiwa.
Ledakan di JW Marriott terjadi pada pukul 07.47, sementara di Ritz Carlton pukul 07.57. Hanya beberapa menit kemudian, saya yang berada ratusan kilometer dari Jakarta sudah menyimak kabar soal ledakan itu, meski tentu saja, belum berupa informasi yang lengkap. Kemungkinan besar Metro TV menerima kabar kilat ini dari pemirsanya. Berita-berita soal ledakan tersebut pada detik-detik awal memang hanya berupa informasi lisan yang selama beberapa menit diulang-ulang.
Presenter Breaking News, selama beberapa menit, selalu mengulang kalimat, "Pemirsa, beberapa waktu yang lalu telah terjadi ledakan di Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Jakarta." Hal semacam ini, meski agak membosankan bagi kita yang menonton, tapi merupakan laku tak terhindarkan dari sebuah organisasi berita yang ingin secepat mungkin mengabarkan sesuatu pada khalayaknya. Pada momen-momen itu, saya kira, pengetahuan para awak redaksi Metro soal ledakan tersebut tak banyak berbeda dengan para penontonnya. Jadi, memang tak ada yang bisa disiarkan selain mengulang kalimat yang sama. Jangankan gambar, informasi lebih banyak soal ledakan itu saja belum didapat.
Beberapa menit kemudian, setelah informasi lisan dari presenternya, Metro mulai menghubungi sejumlah orang yang disebut sebagai saksi mata ledakan. Beberapa orang diwawancarai secara langsung via sambungan telepon. Ini berlangsung dalam hitungan setengah jam lebih. Dan, tetap masih belum ada gambar. Informasi yang dikumpulkan-sekaligus disiarkan langsung pada kita-melalui wawancara langsung ini hanya sepotong-potong, sama sekali tidak sistematis, dan banyak terjadi pengulangan yang mubazir. Hal semacam ini terjadi karena presenter yang melakukan wawancara tidak melontarkan pertanyaan secara sistematis. Seharusnya, pertanyaan-pertanyaan dasar yang mencakup 5W+1H diajukan lebih dulu, baru dilanjutkan dengan persoalan yang lebih mendalam.
Yang sangat saya sayangkan, pada awal-awal pemberitaannya, Metro TV gagal menangkap fakta bahwa pagi itu terjadi dua ledakan di dua tempat yang berbeda. Selama setengah jam lebih, Metro hanya mengabarkan bahwa ledakan terjadi di Hotel Ritz-Carlton, sama sekali tak menyinggung nama JW Marriott. Saya yang menyimak beberapa pemberitaan di stasiun televisi lain sempat bingung: sebenarnya, ada berapa ledakan, di berapa tempat. TV One, televisi berita saingan Metro, lebih tepat menangkap fakta karena sejak awal sudah menyiarkan adanya dua ledakan: satu di JW Marriott, satu di Ritz-Carlton.
Metro TV juga memiliki "cacat akurasi" karena seorang narasumber yang diwawancarainya sempat mengatakan bahwa ledakan di Ritz-Carlton terjadi akibat genset yang meledak. Narasumber yang menyebut informasi ini seorang pekerja kantoran yang kebetulan ada di dekat tempat ledakan. Ia mengatakan, informasi soal genset yang meledak itu didengarnya dari "seorang polisi". Presenter Breaking News Metro TV sempat menyebut informasi ini "seharusnya cukup dapat dipercaya".
TV One memang lebih akurat, tapi sebagai televisi berita, seharusnya TV One malu karena terlambat menyiarkan berita ledakan itu selama lebih setengah jam dari Metro. Ketika Metro sudah mulai menyiarkan berita ledakan, TV One masih tenang-tenang saja dengan acara "Apa Kabar Indonesia"-nya yang membosankan itu. Saya sempat berpikir: apakah para awak TV One tak menyimak Metro, saingan terberatnya itu?
RCTI adalah stasiun televisi ketiga yang menyiarkan berita ledakan. Tapi Trans TV yang pertama kali menayangkan rekaman gambar soal peristiwa itu. Dibandingkan Metro, TV One, dan RCTI yang belum memiliki gambar dan hanya mengandalkan berita melalui wawancara langsung dengan orang-orang yang disebut sebagai "saksi mata"-sesungguhnya, kita tak tak pernah diyakinkan soal kredebilitas sumber-sumber ini-Trans TV menyajikan liputan yang lebih lengkap. Peristiwa ledakan dihadirkan secara lebih baik, dengan rekaman audio visual soal proses evakuasi korban yang mulai menarik empati kita soal dampak ledakan. Ketika Trans TV mulai menayangkan rekaman-rekamannya, stasiun televisi lain masih terus berkutat dengan wawancara telepon.
***
Lepas dari detik-detik awal kejadian, persaingan yang terjadi bukan lagi soal kecepatan. Perlombaan mendapatkan gambar, dan buru-buru memberi cap "eksklusif", merupakan bentuk kompetisi selanjutnya yang dilakukan stasiun-stasiun televisi. Metro TV dan TV One tetap bersaing paling ngotot. Bentuk kompetisi lain adalah menghadirkan "analisis" atas peristiwa ledakan bom tersebut, terutama soal siapa yang berada di balik aksi teror itu. Dalam lomba analisis ini, secara ironis, TV One harus diberi "tropi juara satu".
Melalui mata acara "Apa Kabar Indonesia" dan pelbagai tayangan berita dan talkshownya, TV One memang amat rajin membuat analisis. Bahkan, tema perbincangan di "Apa Kabar Indonesia Pagi" selama beberapa hari pasca-ledakan terus-terusan diberi tajuk "Analisis Peristiwa Bom". Sayangnya, apa yang disebut sebagai "analisis" ini tak lebih dari perbincangan-perbincangan spekulatif dan kadang-kadang bahkan konspiratif. Para narasumber yang diundang kebanyakan adalah orang-orang yang secara tiba-tiba diberi atribusi-atribusi lucu, semisal "pengamat terorisme", "pengamat intelijen", dan "pengamat keamanan". Parahnya, para presenter yang memandu pun kadang-ladang melontarkan pertanyaan-pertanyaan klise, diulang-ulang, dan bahkan konyol.
Saya masih ingat bagaimana seorang pembawa acara "Apa Kabar Indonesia Pagi" bertanya pada Hendropriyono, Mantan Kepala BIN, berapa persen jumlah gedung di Jakarta yang sudah memiliki metal detector? Keesokan paginya, sang pembawa acara yang sama ternyata bertanya pada seorang peneliti LIPI, apa sih sebenarnya kegunaan metal detector? Pertanyaan-pertanyaan tidak cerdas semacam itu bukan sekali-dua diajukan. Orang-orang seperti Andri Jarot dan Indy Rahmawati-dua nama yang belakangan amat sering memandu "Apa Kabar Indonesia Pagi"- sering kali terjebak pada klise-klise tak berguna semacam itu.
Ketimbang melakukan penelusuran investigatif yang menghasilkan fakta-fakta, TV One memang lebih suka mengundang "para pengamat" untuk ditanyai. Bagi saya, ini sebuah kemalasan, dan kalau kecenderungan ini terus-terusan berlanjut, predikat "televisi berita" sebaiknya diganti menjadi "televisi talkshow" saja-mengingat, jumlah talkshow di TV One amat banyak juga kan? Tapi kemalasan semacam itu memang tabiat jurnalisme Indonesia yang sulit dibendung. Lebih suka menanyai narasumber, lalu menjadikan pernyataan narasumber tadi sebagai berita, itulah kemalasan yang saya maksud.
Dalam ihwal tertentu, hal tersebut sama sekali bukan masalah. Tapi dalam peristiwa semacam ledakan bom kemarin, "jurnalisme ludah" semacam itu sungguh membosankan, dan terutama sekali membingungkan. Bagaimanapun, yang dibutuhkan bukan omongan spekulatif yang kabur, konspiratif, atau bombastis. Yang dibutuhkan publik pada masa pasca-teror adalah kejernihan dan kejelasan. Pendeknya, yang dibutuhkan adalah jurnalisme dengan akurasi, bukan jurnalisme yang (hanya) dipenuhi ludah "para pengamat".
Ketika melakukan kajian atas berita-berita Bom Bali I, Eriyanto dan Agus Sudibyo menyimpulkan bahwa kebanyakan media massa di Jakarta lebih suka mengutip komentar "para pengamat" ketimbang melakukan pencarian fakta-fakta di lapangan. Salah satu yang paling sering mengutip para komentator waku itu adalah Harian Republika. Satu penyebabnya karena kala itu fakta-fakta yang ditemukan polisi cenderung "memojokkan" citra umat Islam sehingga, sebagai harian yang memihak Islam, Republika berusaha menyajikan berita-berita dengan perspektif beda.
Mereka yang rutin membaca Republika pada masa-masa itu mungkin akan ingat bahwa harian itu berusaha mengarahkan opini tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam Bom Bali I. Karena fakta penyidikan polisi tak mendukung opininya, Republika mengutip komentar-komentar dari para tokoh, yang dianggap sebagai "pengamat", yang mendukung teori konspirasi keterlibatan Amerika Serikat. Teori konspirasi semacam itu akhirnya tenggelam dengan sendirinya, dan kini orang tahu harus menyalahkan siapa atas bom di Bali. Barangkali, kebenaran yang ditemukan jurnalisme soal Bom Bali I dan kita pegang hari ini memang bukan kesahihan yang paripurna, tapi kualitas semacam itu memang bukan tujuan jurnalisme.
Yang terjadi pada Republika tentu berbeda dengan TV One. Republika mengutip para komentator karena alasan ideologis, sementara TV One melakukannya dengan alasan yang kita tak sepenuhnya tahu. Mungkin demi bombasme, atau memang "analisis" semacam itulah yang mereka bisa tampilkan. Yang jelas, keduanya dipenuhi "jurnalisme ludah" yang tidak menyehatkan bagi publik. [Haris Firdaus, politikana.com]